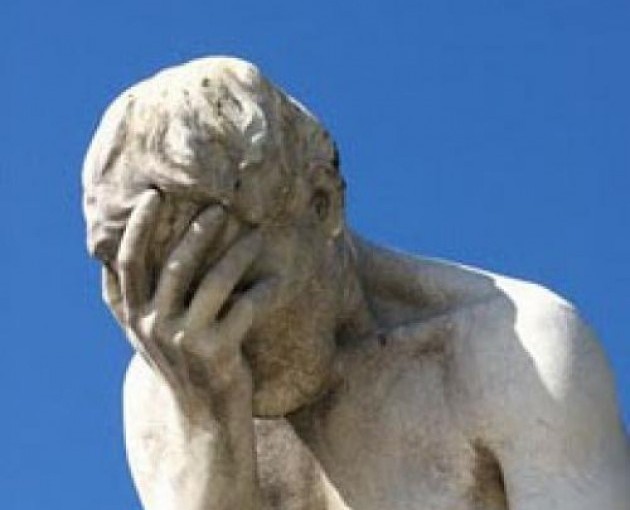Pada salah satu pertemuan kuliah dengan Prof. DR. Jum’ah Ali Abdul Qadir (almarhum), beliau menceritakan pengalamannya ketika mengajar di Universitas Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah khusus untuk perempuan:
“Suatu kali ketika mengajarkan tafsir surat Ar-Rum ayat 4, saya bertanya kepada salah seorang mahasiswi, apa perbedaan antara kalimat (بِضْع) “bidh’un” dengan meng-kasrah-kan huruf ba’ dan (بُضْع) “budh’un” dengan men-dhammah-kan huruf ba’?
Jawaban mahasiswi itu sangat mencengangkan. Jawaban yang menunjukkan dia seorang perempuan yang cerdas, paham, dihiasi oleh rasa malu dan kehormatan diri.
Dia berkata:
“Adapun “bidh’un” adalah bilangan antara 3 sampai 9, sedangkan “budh’un” adalah sesuatu yang kita malu untuk menyebutkannya di depan orang lain.”
Jawaban ini sangat berkesan bagi saya sampai hari ini, ujar beliau melanjutkan cerita. Demikianlah seharusnya seorang yang mempunyai harga diri, ia harus menjaga bahasanya dari mengucapkan perkataan fulgar dan porno. Terutama dalam majlis ilmu dan forum-forum resmi seperti itu. Lebih-lebih lagi bila di sana hadir laki-laki dan perempuan. Hendaknya dijaga perasaan perempuan yang lebih halus dan lebih pemalu dari pada laki-laki.
Sekalipun seorang guru atau ustadz dituntut untuk menyampaikan sesuatu yang memalukan bila disebut dengan terang-terangan,seperti permasalahan yang berhubungan dengan perkara fikih, ia akan berusaha untuk mencari kosa kata yang bisa mewakili apa yang ia maksud, tapi terjauh dari bahasa yang tidak pantas. Namun orang yang mendengar tetap paham apa maksud perkataan itu.”
Apa yang diajarkan oleh DR. Jum’ah Ali ini sebenarnya penjelasan dari ajaran Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah. Di mana Al-Qur’an selalu memilih kosa kata yang sangat halus untuk mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan laki-laki dan perempuan atau suami-istri.
Contoh, ayat Al-Qur’an mengibaratkan istri itu dengan sawah ladang, dan pergaulan dengannya dipakai istilah bercocok tanam.
نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.” (Al-Baqarah: 223)
Maha Mulia Allah yang menggunakan kalimat yang sangat mulia karena Al-Qur’an akan dibaca dalam shalat dan tilawah.
Rasulullah pernah ditanya tentang seorang suami yang telah menceraikan istrinya sampai talak tiga, lalu mantan istrinya itu menikah dengan laki-laki lain. Sebelum digauli oleh suami barunya, ia ditalak oleh suami barunya itu. Apakah dengan demikian dia sudah halal menikah lagi dengan suami lamanya?
Rasulullah menjawab:
«لاَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ»
“Belum, sampai suami barunya itu mencicipi madunya sebagaimana suaminya yang pertama telah mencicipinya”. (HR. Bukhari Muslim)
Perhatikanlah bagaimana bersih dan indahnya bahasa Rasulullah yang mengibaratkannya dengan madu.
Aisyah menceritakan, suatu kali seorang perempuan bertanya kepada Nabi, bagaimana caranya bersuci dari haid? Rasulullah menjawab, “Ambillah sepotong kapas yang sudah diolesi harum-haruman, kemudian bersihkan dengannya.”
Perempuan itu bertanya lagi, “Bagaimana cara membersihkannya?”
Rasulullah menjawab, “Bersihkanlah dengannya!”
Perempuan itu masih bertanya lagi, “Bagaimana?”
Lalu Rasulullah berkata sambil menutupi wajahnya dengan pakaian, “Subhanallah, bersihkanlah!”
Kemudian Aisyah melanjutkan ceritanya: Lalu aku menarik perempuan itu dengan kuat dan mengatakan kepadanya, “Bersihkan bekas darahnya dengan kapas itu!”
Meskipun pertanyaan perempuan itu sangat urgent demi kesucian dan kesempurnaan ibadahnya, namun Rasulullah tetap memakai bahasa yang sangat halus, yang paling pantas dengan fitrah pemalunya seorang perempuan. Rasulullah tidak hanya mementingkan bagaimana pesan tersampaikan, tapi juga menimbang cara dan kalimat yang paling terhormat.
Amat disayangkan pada masa kita ini, sebagian ustadz dan da’i yang menyampaikan ceramah kurang memperhatikan hal ini. Bahkan seperti disengaja untuk memilih kosa kata fulgar demi membuat jama’ah tertawa. Bagaimana kita akan mengajari umat perihal malu bila kalimat para penceramahnya tanpa sengaja mengikis malu sedikit demi sedikit. Atau dia bagaikan orang yang tidak ada malu di depan jama’ahnya.
Bukankah ceramahnya itu juga akan didengar oleh anak-istri, ipar-besan, dan keluarga serta handai tolannya. Tidakkah ia malu dengan mereka semua?
Dalam sebuah hadits yang sangat masyhur Rasulullah bersabda:
«الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ»
“Malu itu sebagian dari iman.” (HR. Bukhari Muslim)
Ya Allah, karuniakan kami rasa malu yang sebenarnya.