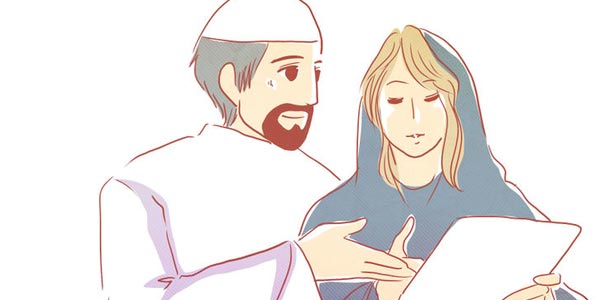Menjelang Idul Fitri, masyarakat berbondong menukarkan uangnya dengan uang pecahan baru. Tradisi berbagi kepada kerabat dengan pecahan uang baru sudah terjadi selama bertahun-tahun.
Memanfaatkan peluang ini, muncul banyak jasa penukaran uang pecahan baru. Ada yang resmi dari Bank Indonesia, ada pula yang dilakukan masyarakat dengan membuka jasa penukaran di pinggir jalan. Lalu, bagaimana sebenarnya pandangan para ulama terhadap penukaran uang dengan uang pecahan baru?
Program Studi Ekonomi Syariah IPB pernah mengeluarkan pandangan soal ini. Disebutkan, pada dasarnya jual beli mata uang yang diistilahkan dengan tijarah an-naqd atau al-sharf dibolehkan dalam Islam dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi.
Kebolehan tersebut didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, “Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus semisal dengan semisal, sama dengan sama (beratnya/takarannya), dan dari tangan ke tangan (kontan). Maka jika berbeda jenis-jenisnya, juallah sesuka kamu asalkan dari tangan ke tangan (kontan).” (HR Muslim nomor 1210; a-Tirmidzi III/532; Abu Dawud III/248).
Emas dan perak pada hadis di atas dapat dihukumkan dengan mata uang pada saat ini. Berdasarkan hadis di atas, jika terjadi tukar-menukar antara dua jenis yang sama yaitu emas dengan emas atau perak dengan perak, maka harus memiliki berat atau timbangan yang sama, dan penyerahannya dilakukan secara kontan.
Adapun pertukaran antara dua jenis yang berbeda yaitu emas dengan perak, maka boleh saja ada kelebihan dalam berat maupun timbangan namun harus tetap dilakukan secara kontan. Jika uang kertas Rp 10 ribu hendak ditukar dengan pecahan yang lebih kecil, misal Rp 1.000 maka harus berjumlah sebanyak sepuluh lembar uang ribuan.
Prodi Ekonomi Syariah IPB menyebutkan, dalam praktik tukar uang ini ada potensi riba yang mengancam. Jika si penukar mendapatkan jumlah uang lebih sedikit dari yang ditukar, maka hal ini jatuh kepada hukum riba yang dilarang.
MUI Jawa Timur juga pernah mengeluarkan pendapat soal larangan penukaran uang baru. MUI Jawa Timur menemukan praktik penukaran uang di pinggir jalan sudah mematok penukaran Rp 100 ribu dengan pecahan Rp 10 ribu, penukar hanya mendapatkan Rp 90 ribu. Penukaran jenis ini yang dilarang.
Sementara jika penukaran nilai yang diberikan sama, lalu si penukar memberi uang jasa setelah penukaran dengan jumlah yang tidak ditentukan, hal ini diperbolehkan.
Pandangan ini juga diamini MUI Kudus. Menurut MUI Kudus, bisnis penukaran uang tidak selamanya diharamkan, karena harus disesuaikan dengan akad transaksinya.
Jika akad transaksinya penyedia jasa mengungkap secara langsung permintaan uang jasa atas jerih payahnya mengantre untuk menukar uang di bank, maka transaksinya dianggap sah.
Artinya, masyarakat yang membutuhkan uang pecahan menyerahkan uangnya sesuai dengan jumlah uang pecahan yang dibutuhkan. Sedangkan besarnya kompensasi jasa atas jerih payahnya mengantre untuk mendapatkan uang pecahan di bank harus sesuai kesepakatan keduanya.
Namun, jika sudah langsung dipotong dalam penukaran, sehingga si penukar mendapat uang yang lebih sedikit maka hal tersebut yang harus diwaspadai. Apalagi si penjual sudah mematok paket-paket penukaran yang tidak bisa ditawar.
Penukaran uang sejenis, baru diperbolehkan jika pertukarannya tidak disertai lebihan. Artinya, dengan nilai yang sama. Misalnya, uang 100 ribu ditukar dengan pecahan 5.000-an yang nilainya juga 100 ribu tanpa dikurangi atau dilebihkan. Bentuk pertukaran uang yang semacam ini boleh.
Adapun sesudah pertukaran itu terjadi, jika pihak yang menukar ingin berterima kasih dengan memberikan sejumlah uang sebagai balas jasa kepada pihak yang telah menukarkan uang, hal itu sah atau boleh selama besarannya tidak ditentukan sebelumnya dan tidak dipersyaratkan.
Din Syamsuddin pernah mengatakan, jasa penukaran uang tersebut masih wajar selama tidak ada unsur paksaan dari penyedia jasa. Dengan konsep fikih antarodhin min kum antara masing-masing pihak sukarela, maka transaksi jasa semacam itu sah secara syariah.
Namun, kata Din, pengecualian terjadi manakala ada unsur paksaan, penipuan, dan kebohongan dalam transaksi jasa tersebut. Selama potongan yang dikenakan kepada konsumen diberitahu oleh penyedia jasa dan konsumen menerima ketentuan tersebut, maka sudah sah secara agama.
Oleh: Hafidz Muftisany
sumber: Repblika ONline
Baca juga: Waspadai Transaksi Riba Saat Tukar Uang Receh di Jalan