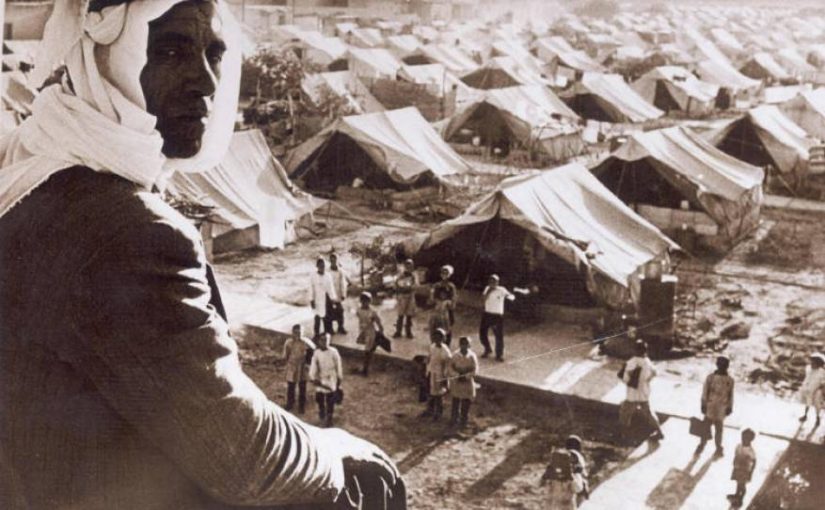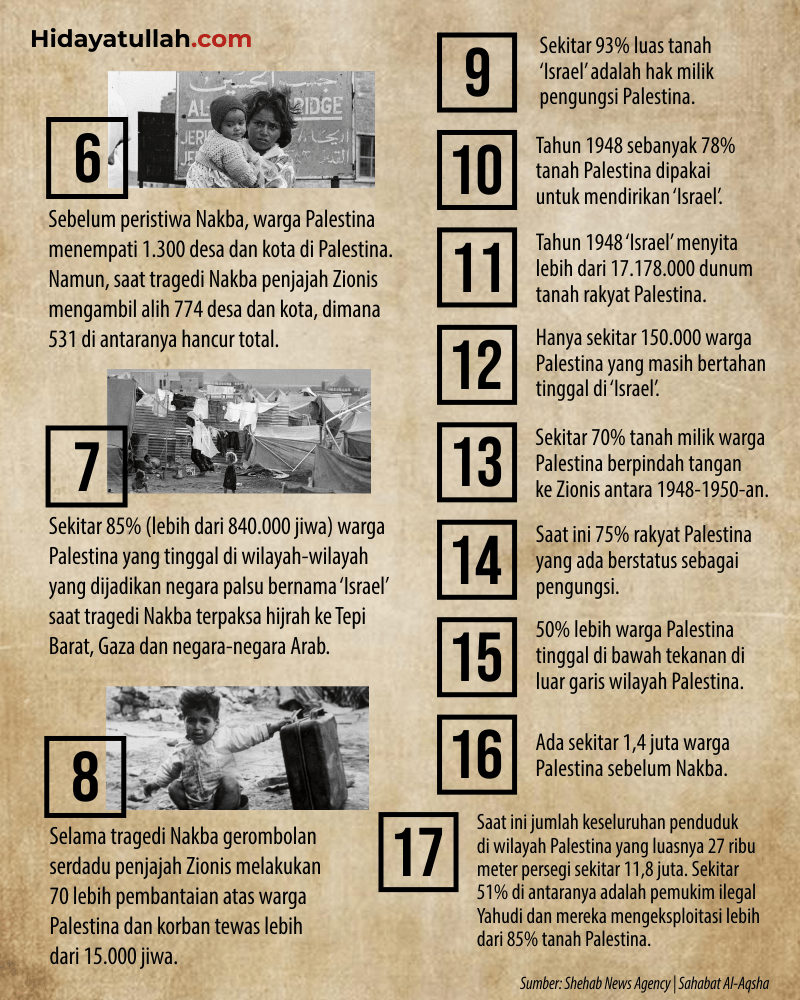Pembahasan mengenai golongan orang yang termasuk fakir atau miskin ini terkait dengan banyak hal. Diantaranya masalah zakat, fidyah, dan kafarah. Lalu siapa saja yang tergolong orang miskin atau fakir?
Definisi miskin telah disebutkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallambersabda,
ليسَ المِسْكِينُ الذي يَطُوفُ علَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ واللُّقْمَتَانِ، والتَّمْرَةُ والتَّمْرَتَانِ، ولَكِنِ المِسْكِينُ الذي لا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، ولَا يُفْطَنُ به، فيُتَصَدَّقُ عليه ولَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ
“Orang miskin bukan hanya yang berkeliling meminta-minta kepada orang lain lalu mereka diberi makanan sesuap atau dua suap, atau sebiji-dua biji kurma. Namun orang miskin adalah orang yang tidak mendapatkan kecukupan untuk menutupi kebutuhannya. Dan ia tidak menampakkan kemiskinannya sehingga orang-orang bersedekah kepadanya, dan ia juga tidak minta-minta kepada orang lain” (HR. Bukhari no. 1479, Muslim no.1039).
Yang dimaksud oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallamdalam hadis di atas adalah orang miskin yang muta’affif (menjaga kehormatan). Sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain,
إنَّما المِسْكِينُ الذي يَتَعَفَّفُ، واقْرَؤُوا إنْ شِئْتُمْ يَعْنِي قَوْلَهُ: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إلْحَافًا}
“Sesungguhnya orang miskin adalah yang menjaga kehormatannya. Bacalah firman Allah ta’ala: [mereka tidak meminta-minta kepada manusia dengan memaksa] (QS. Al-Baqarah: 273)” (HR. Bukhari no. 4539).
Dalam riwayat lain,
ولَكنَّ المسْكينَ المتعفِّفُ وفي زيادةٍ ليسَ لَهُ ما يستغني بِهِ الَّذي لا يسألُ ولا يُعلمُ بحاجتِهِ فيتصدَّقَ عليْهِ
“Orang miskin yang muta’affif (menjaga kehormatan) adalah yang tidak mendapatkan kecukupan untuk menutupi kebutuhannya. Dan ia tidak meminta-minta, tidak menampakkan kemiskinannya sehingga orang-orang bersedekah kepadanya” (HR. Abu Daud no. 1632, didha’ifkan oleh Al-Albani dalam Dha’if Abu Daud).
Namun ‘ala kulli haal, dari hadis ini, para ulama menyimpulkan kaidah umum tentang patokan miskin, yaitu orang yang penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
Disebutkan dalam Mu’jam Al-Wasith,
المِسْكِينُ : من ليس عنده ما يكفي عياله، أَو الفقير
“Miskin adalah orang yang tidak mendapati penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Disebut juga dengan fakir”.
Dalam Mu’jam Musthalahat Fiqhiyyah juga disebutkan,
الذي لا يجد قوته، وقيل: هو الذي لا يملك قوت يومه والفقير من لا يملك قوت سنته، لكن على كل حال حكمهما واحد
“Orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Sebagian ulama mengatakan: orang yang tidak dapat memenuhui kebutuhan pokoknya untuk sehari. Sedangkan fakir adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya untuk setahun. Namun ‘ala kulli haal, fakir dan miskin dianggap sama dalam hukum”.
Contohnya, orang yang kebutuhan pokoknya sehari adalah 100 ribu rupiah, namun penghasilannya hanya 75 ribu rupiah. Maka orang ini tergolong miskin.
Dan cara mengetahui apakah seseorang itu termasuk miskin atau tidak boleh dengan dua cara:
- Diketahui secara pasti bahwa penghasilan orang tersebut kurang dari kebutuhannya
- Berdasarkan ghalabatuz zhan (sangkaan kuat) bahwa penghasilan orang tersebut kurang dari kebutuhannya
Al-‘Allamah Al-Buhuti rahimahullah menjelaskan,
ولا يجوز دفع الزكاة إلا لمن يعلم أنه من أهلها و يظنه من أهلها؛ لأنه لا يبرأ بالدفع إلى من ليس من أهلها، فاحتاج إلى العلم به لتحصل البراءة، والظن يقوم مقام العلم؛ لتعذر أو عسر الوصول إليه
“Dan tidak boleh memberikan zakat kecuali kepada orang yang diketahui pasti bahwa ia termasuk yang berhak menerimanya, atau disangka kuat ia termasuk yang berhak menerimanya. Maka di sini dibutuhkan pengetahuan yang pasti sehingga muzakki bisa dikatakan lepas dari tanggungan zakat. Atau sangkaan kuat yang kadarnya selevel dengan ilmu, jika memang ada uzur dan kesulitan untuk memastikan” (Kasyful Qina’, 2/339).
Perbedaan antara fakir dan miskin
Ulama khilaf tentang perbedaan antara fakir dan miskin, dan manakah yang lebih membutuhkan antara keduanya?
Al-Qurthubi rahimahullah mengatakan,
أن المراد بالفقير: المحتاج المتعفف الذي لا يسأل، والمسكين: المحتاج المتذلل الذي يسأل
“Yang dimaksud fakir adalah orang yang membutuhkan dan ia menjaga kehormatannya dengan tidak minta-minta. Sedangkan miskin adalah orang yang membutuhkan yang menghinakan dirinya dengan minta-minta” (Tafsir Al-Qurthubi, 14/308).
Berbeda lagi dengan Al-Khathabi rahimahullah, beliau menjelaskan Abu Hurairah di atas, dengan mengatakan,
في الحديث دليل على أن المسكين – في الظاهر عندهم والمتعارف لديهم- هو السائل الطواف
“Hadis ini menunjukkan bahwa miskin adalah orang yang suka berkeliling minta-minta (berdasarkan apa yang dipahami oleh para salaf)” (Ma’alimus Sunan, 2/232).
Dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar (hal. 144) disebutkan: “fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa untuk menutupi kebutuhan pokok dirinya dan kebutuhan pokok keluarganya, berupa makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Ia tidak mendapati apa-apa. Atau ia mendapat kurang dari 50% kebutuhan pokoknya. Maka orang seperti ini hendaknya diberi zakat untuk mencukupi kebutuhannya selama 1 tahun penuh.
Miskin adalah orang yang mendapati penghasilan yang mencukupi 50% kebutuhan pokoknya atau lebih (namun tidak sampai genap 100%). Seperti orang yang penghasilannya 100 riyal, namun ia butuh 200 riyal. Maka orang seperti ini juga hendaknya diberi zakat untuk mencukupi kebutuhannya selama 1 tahun penuh”.
Ringkasnya, khilaf ulama dalam masalah ini menjadi 3 pendapat:
Pendapat pertama, yang menyatakan bahwa fakir itu lebih parah dan membutuhkan daripada miskin.
Pendapat kedua, yang menyatakan bahwa miskin itu lebih parah dan membutuhkan daripada fakir.
Pendapat ketiga, yang menyatakan bahwa fakir dan miskin itu sama.
Yang rajih, fakir dan miskin itu jika disebutkan bersendirian maka ia sama, namun ia jika disebutkan bergandengan maka fakir lebih parah dan lebih membutuhkan daripada miskin.
Syekh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin menjelaskan, “Perbedaan antara fakir dan miskin, jika keduanya disebutkan bersamaan, maka fakir lebih membutuhkan daripada miskin. Karena kata ‘fakir’ diambil dari kata al-faqr yang artinya: tidak ada apa-apa. Orang Arab biasa berkata: hadza ardhun faqrun, maksudnya: ini tanah yang kosong tidak ada tumbuhan … adapun jika disebutkan bersendirian maka maknanya sama ” (Fatawa Nurun ‘alad Darbi, 3/206).
Baik fakir maupun miskin, keduanya sama-sama berhak diberi zakat, fidyah dan juga kafarah. Karena mereka berdua sama secara hukum. Syekh Abdul Aziz bin Baz, mengatakan,
المسكين هو الفقير الذي لا يجد كمال الكفاية، والفقير أشد حاجة منه، وكلاهما من أصناف أهل الزكاة
“Miskin adalah orang fakir yang penghasilannya tidak sampai kadar mencukupi. Dan fakir itu lebih butuh daripada miskin. Namun keduanya termasuk golongan penerima zakat” (Majmu’ Fatawa wa Maqalat Mutanawwi’ah, 14/265).
Orang yang punya aset harta apakah disebut miskin?
Jika ada orang yang mengaku miskin, namun ia memiliki rumah, atau memiliki smart phone, atau memiliki mobil, dan semisalnya, apakah ia tetap dianggap miskin dan boleh menerima zakat dan fidyah?
Allah ta’ala menyebutkan perkataan Nabi Khidhir ‘alaihissalam,
أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا
“Adapun perahu itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera” (QS. Al-Kahf: 79).
Dalam ayat ini disebutkan orang-orang miskin mereka memiliki perahu. Padahal kita tahu perahu adalah kendaraan yang harganya tidak murah. Namun mereka gunakan perahu ini untuk mencari penghasilan. Maka tetap mengubah status mereka sebagai orang miskin.
Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan,
وجملة ذلك أنه إذا ملك مالا تتم به كفايته من غير الأثمان، فان كان مما لا تجب فيه الزكاة كالعقار ونحوه لم يكن ذلك مانعا من أخذها. نص عليه أحمد فقال في رواية محمد بن الحكم: إذا كان له عقار يستغله أو ضيعة تساوي عشرة آلاف أو أقل أو أكثر لا تقيمه يأخذ من الزكاة، وهذا قول الثوري والنخعي والشافعي وأصحاب الرأي
“Kesimpulannya, jika ia memiliki harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan bukan berupa uang, jika harta tersebut termasuk harta yang tidak wajib dizakati, seperti al ‘aqar (aset pasif) atau semisalnya, maka ini tidak menghalangi dia untuk menerima zakat. Pendapat ini ditegaskan oleh Imam Ahmad. Dalam riwayat dari Muhammad bin Al-Hakam, Imam Ahmad berkata: “Jika ‘aqar itu terus ia manfaatkan atau ia memiliki tanah yang disewakan seharga 10.000 riyal atau kurang dari itu atau lebih dari itu maka ia boleh menerima zakat”. Ini juga pendapat Ats-Tsauri, An-Nakha’i, Asy-Syafi’i dan Ash-habur Ra’yi (Hanafiyah)” (Asy-Syarhul Kabir, 2/687).
Dari penjelasan beliau, bisa kita simpulkan beberapa poin:
- Jika orang miskin memiliki aset, dan aset tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, dan penghasilannya tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, maka ia tetap dikatakan orang miskin dan boleh menerima zakat. Seperti orang yang memiliki rumah dan tanah, namun rumah dan tanah tersebut ia gunakan untuk tempat tinggalnya. Maka ia boleh menerima zakat.
Syekh Abdul Aziz Bin Baz juga pernah ditanya, “Apakah boleh saya memberi zakat mal kepada seorang yang sudah menikah, ia memiliki anak perempuan yang masih kecil, dan ia memiliki mobil taksi. Mobil taksi tersebut ia gunakan untuk mencari penghidupan rata-rata sebesar 700 junaih. Dan terkadang di bulan yang lain ia tidak gunakan mobil tersebut karena ia juga bekerja sebagai pegawai pemerintah dengan gaji 150 junaih”.
إذا كنت تعلمين أنه فقير، وأنه عرض له حاجة وفقر فلا بأس، وإلا فالذي عنده أسباب تقوم بحاله لا يعطى الزكاة
“Jika anda tahu pasti dia adalah orang yang fakir, dan ia memang orang yang membutuhkan, maka tidak mengapa memberi zakat kepadanya. Jika tidak demikian, dan orang tersebut punya sebab-sebab lain untuk memenuhi kebutuhannya, maka ia tidak diberi zakat” (Fatawa Nurun ‘alad Darbi, 15/326).
- Jika orang miskin memiliki aset yang sifatnya sekunder atau tersier, bukan untuk kebutuhan primernya, maka ia tidak dikatakan miskin dan tidak boleh menerima zakat. Seperti orang yang memiliki mobil namun bukan untuk mencari penghasilan, orang yang memiliki rumah lain selain rumah tinggalnya, orang yang memiliki tanah selain yang ia tinggali, dan semisalnya.
Syekh Abdul Aziz Bin Baz ditanya tentang orang yang punya banyak hutang, namun ia baru membeli rumah baru, apakah ia boleh diberi zakat sebagai gharim (orang yang berhutang)? Beliau menjawab,
إذا كان اشترى البيت الجديد للتجارة أو لمزيد الدنيا وعنده بيت يكفيه فلا يستحق الزكاة، بل يبيع بيته الجديد ويوفي ما عليه من الدين، أو يلتمس ذلك من جهات أخرى؛ لأنه ليس فقيراً
“Jika orang tersebut membeli rumah yang baru untuk usaha atau untuk menambah perbendaharaan dunia dia, sedangkan ia sudah memiliki rumah lain yang mencukupinya (untuk tempat tinggal), maka ia tidak berhak menerima zakat. Bahkan seharusnya ia menjual rumah barunya tersebut dan melunasi hutangnya. Atau mencari uang dengan cara lainnya. Karena ia bukan orang fakir” (Fatawa Nurun ‘alad Darbi, 15/330).
- Jika orang miskin memiliki aset yang wajib dizakati, seperti emas dan perak, barang dagangan yang nilainya besar, dan semisalnya, maka ia tidak dikatakan miskin dan tidak boleh menerima zakat.
Maka jelaslah bahwa orang mengaku miskin namun ia memiliki aset harta tidak bisa dipukul rata statusnya. Ada yang tetap berhak menerima zakat dan ada yang tidak berhak menerima zakat.
Jika yang diberi zakat ternyata orang yang berkecukupan
Ketika seseorang sudah membayarkan zakatnya kepada orang yang berhak menerimanya, setelah berupaya memastikan bahwa orang tersebut adalah orang yang layak menerima zakat, kemudian jika setelah itu baru diketahui ternyata si penerima zakat tersebut adalah orang berada dan bukan orang miskin. Bagaimana status zakatnya?
Syekh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin rahimahullah menjelaskan,
وذهب بعض أهل العلم : إلى أنه إذا دفعها إلى من يظن أنه أهل بعد التحري ، فبان أنه غير أهل فإنها تجزئه ؛ حتى في غير مسألة الغني ؛ أي: عموما ؛ لأنه اتقى الله ما استطاع لقوله تعالى: ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) البقرة/ 286 ، والعبرة في العبادات بما في ظن المكلف بخلاف المعاملات فالعبرة بما في نفس الأمر، ويصعب أن نقول له : إن زكاتك لم تقبل مع أنه اجتهد، والمجتهد إن أخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران
وهذا القول أقرب إلى الصواب أنه إذا دفع إلى من يظنه أهلا مع الاجتهاد والتحري فتبين أنه غير أهل فزكاته مجزئة
“Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, setelah berupaya untuk memastikan ia berhak. Kemudian jika setelah dibayarkan, baru diketahui fakta bahwa ia orang yang tidak berhak menerima zakat, maka zakatnya tetap sah. Dan kaidah ini berlaku juga untuk masalah-masalah lain, secara umum. Karena orang yang membayar zakat tadi telah berusaha bertakwa kepada Allah semaksimal kemampuannya. Allah ta’ala berfirman (yang artinya) : “Bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan kalian” (QS. Al-Baqarah: 286). Dan yang dianggap dalam ibadah adalah keadaan yang diketahui oleh mukallaf. Berbeda dengan urusan muamalah, yang dianggap adalah fakta senyatanya. Sehingga sulit untuk mengatakan “zakat anda tidak sah”. Padahal ia telah berijtihad. Dan orang yang berijtihad itu jika keliru maka dapat satu pahala, dan jika benar ia dapat dua pahala.
Ini adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Yaitu bahwa jika seseorang menyerahkan zakat kepada orang yang ia sangka berhak menerimanya, setelah berupaya untuk memastikan, kemudian ternyata si penerima tidak layak, maka zakatnya tetap sah” (Syarhul Mumthi‘, 6/264).
Wallahu waliyyut taufiq was sadaad.
Penulis: Yulian Purnama
Artikel: Muslim.or.id
Simak selengkapnya disini. Klik https://muslim.or.id/65814-siapakah-orang-yang-termasuk-fakir-miskin.html