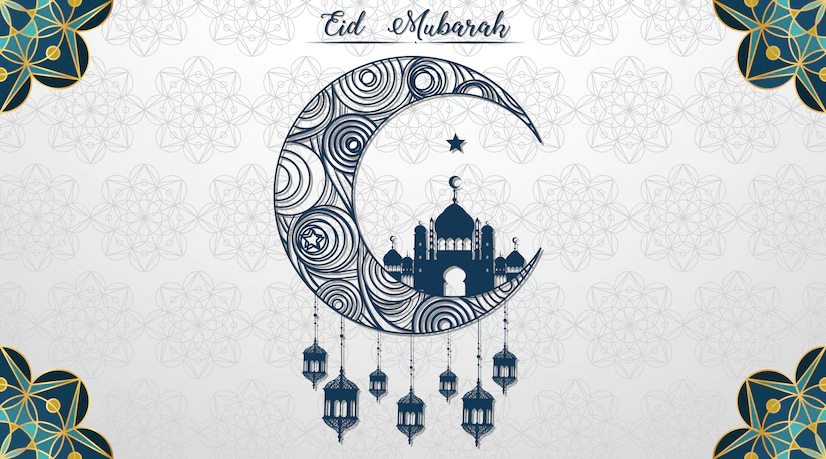Di antara hal-hal yang menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan adalah turunnya Al-Qur’an Kalamullah di bulan tersebut. Allah Ta’ala berfirman,
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَ الْفُرْقَانِ
“Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata yang menunjuk kepada kebenaran, yang membedakan antara yang haq dan yang batil.” (QS. Al-Baqarah: 185)
Di ayat yang lain. Allah Ta’ala menyebutkan,
اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنٰهُ فِىۡ لَيۡلَةِ الۡقَدۡر
“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur’an) pada malam qadar.” (QS. Al-Qadr: 1).
Namun di banyak ayat yang lain serta melalui kisah perjalanan hidup Nabi kita, dapat diketahui bahwa Al-Quran ini tidaklah turun secara spontan pada satu waktu kepada Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wasallam, melainkan turun secara bertahap dan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan dan kejadian yang terjadi saat itu. Allah Ta’ala berfirman,
وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلاً
“Dan Al-Qur’an (Kami turunkan) berangsur-angsur agar Engkau (Muhammad) membacakannya kepada manusia perlahan-lahan dan Kami menurunkannya secara bertahap.” (QS. Al-Isra’: 106)
Hal ini juga terbukti di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Zaid bin Tsabit radhiyallahu ‘anhu, ia menceritakan tentang bagaimana turunnya salah satu ayat yang menjelaskan keutamaan orang yang ikut di dalam peperangan,
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْلَى عَلَيْهِ { لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ } { وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ } فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهْوَ يُمِلُّهَا عَلَيَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ وَكَانَ أَعْمَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرُضَّ فَخِذِي ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ { غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ }
“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mendiktekan kepadanya ayat (yang artinya), ‘Tidaklah sama antara orang mukmin yang tidak ikut berperang’ ‘dan mereka yang berjihad fii sabilillah.’ (QS. An-Nisa: 95) Kemudian datang kepadanya Ibnu Ummi Maktum dan beliau masih mendiktekannya kepadaku. Lalu ia (Ibnu Ummi Maktum) berkata, ‘Wahai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, seandainya saya mampu untuk berjihad, niscaya saya akan berjihad’.
Dan ia adalah orang yang buta. Kemudian Allah menurunkan (wahyu kembali) kepada Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wasallam dan pahanya berada di atas pahaku hingga terasa berat bagiku, hampir aku merasa takut pahaku patah. Kemudian terhilangkan kesusahannya, dan Allah Ta’ala menurunkan ayat (yang artinya), ‘Kecuali orang-orang yang mempunyai halangan‘.” (HR. Bukhari no. 4226).
Dari pemaparan ayat-ayat dan hadis di atas, seringkali seorang muslim menjadi bingung, bagaimana menjamak dan menarik kesimpulan dari ayat-ayat yang dhahir-nya mengandung kontradiksi tersebut. Di beberapa ayat dijelaskan bahwasannya Al-Qur’an diturunkan sekaligus pada malam lailatul qadar, di ayat yang lain disebutkan bahwa ia turun secara bertahap dan berangsur-angsur. Padahal tidak akan ada kontradiksi di dalam Al-Qur’an, karena anggapan seperti ini mengharuskan salah satunya adalah dusta dan itu mustahil terjadi pada berita-berita Allah Subhanahu wa Ta’ala. Allah Ta’ala berfirman,
وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا
“Dan siapakah orang yang lebih benar perkataan(nya) daripada Allah.” (QS. An-Nisa’: 87)
Al-Quran turun melalui beberapa tahapan
Semua kitab samawi yang lain turun secara spontan dan sekaligus kepada Nabi yang menerima. Sedangkan menurut pendapat kebanyakan ulama, dan ini merupakan pendapat yang kuat, Al-Quran mengalami beberapa tahapan sebelum sampai kepada Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam.
Tahap pertama, Allah Ta’ala turunkan Al-Quran dan Allah simpan di Lauhul Mahfudz secara sekaligus. Sebagaimana firman Allah Ta’ala,
بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ
“Bahkan (yang didustakan mereka itu), ialah Alquran yang mulia yang (tersimpan) di Lauhul Mahfuzh.” (QS. Al-Buruj: 21-22).
Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, “yang (tersimpan) di Lauhul Mahfuzh.” Maksudnya (bahwa Al-Quran) di tempat tertinggi dan terjaga dari adanya penambahan, pengurangan, penyelewengan, dan penggantian.” (Tafsir Ibnu Katsir, 4: 497-498)
Tetapi kapan saatnya serta bagaimana caranya tidak seorang pun mengetahui kecuali Allah Ta’ala.
Tahap kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuzh ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Hal ini terjadi pada malam lailatul qadar secara sekaligus dan satu waktu. Tahap inilah yang sejalan dengan firman Allah Ta’ala yang artinya, “Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur’an) pada malam qadar.” (QS. Al-Qadr: 1).
Tahap ketiga, barulah Al-Qur’an ini turun secara bertahap selama 23 tahun kepada nabi kita melalui malaikat Jibril ‘alaihissalam. Turunnya ayat-ayat kalamullah secara bertahap ini memiliki hikmah yang sangat besar. Di antaranya sebagaimana firman Allah Ta’ala,
وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَٰحِدَةً ۚ كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِۦ فُؤَادَكَ ۖ وَرَتَّلْنَٰهُ تَرْتِيلًا
“Berkatalah orang-orang yang kafir, “Mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?” Demikianlah supaya Kami perkuat hatimu dengannya dan Kami membacanya secara tartil.” (QS. Al-Furqan: 32).
Dengan turunnya ayat-ayat Al-Qur’an ini secara berangsur-angsur, maka ia semakin mudah terjaga dan terpelihara. Dengan cara seperti itulah pemahaman terhadap setiap ayat dapat dicerna dengan baik serta mudah untuk dihafalkan.
Hikmah lainnya, Al-Quran merupakan solusi hukum. Sehingga ia turun bertahap menyesuaikan kondisi ketika itu, sebagai contoh dalam masalah penghapusan beberapa tradisi Arab seperti minum minuman keras, maka jelas itu tidak bisa dilakukan secara sekaligus, namun harus secara bertahap dan berangsur-angsur.
Proses penyampaian Al-Quran melalui malaikat Jibril
Kaum mukminin juga harus mengimani dan meyakini bahwa wahyu Al-Quran tidaklah turun kepada Nabi Muhammad secara langsung, namun harus melalui perantara malaikat Jibril ‘alaihissalam. Dan malaikat Jibril tidaklah turun kecuali atas perintah Allah Ta’ala. Allah Ta’ala berfirman,
قُلۡ نَزَّلَہٗ رُوۡحُ الۡقُدُسِ مِنۡ رَّبِّکَ بِالۡحَقِّ
“Katakanlah (wahai Muhammad), Ruhulkudus (Jibril) menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran.” (QS. An-Nahl: 102).
Allah Ta’ala juga berfirman,
قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ
“Katakanlah (Muhammad), “Barangsiapa menjadi musuh Jibril, maka (ketahuilah) bahwa dialah yang telah menurunkan (Al-Quran) ke dalam hatimu dengan izin Allah.” (QS. Al-Baqarah: 97)
Di ayat yang lain, Allah Ta’ala juga mengatakan,
وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ العَالَمِينَ * نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ
“Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin (Jibril) ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan.” (QS. Asy-Syuara’: 192-194).
Mereka yang mengaku beriman kepada Allah juga harus meyakini, bahwa Malaikat Jibril ‘alaihissalam sebelum menyampaikan wahyu tersebut kepada Nabi Muhammad, ia telah mendengar langsung wahyu tersebut dari Allah Ta’ala, kemudian barulah ia menyampaikan wahyu tersebut kepada Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wasallam. Nabi Shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda,
إذا أراد الله تعالى أن يُوحي بالأمر تكلَّم بالوحي، أخذت السَّماوات منه رجفة -أو قال: رعدة- شديدة؛ خوفًا من الله ، فإذا سمع ذلك أهلُ السَّماوات صعقوا وخرُّوا لله سُجَّدًا، فيكون أول مَن يرفع رأسه جبريل، فيُكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمرّ جبريل على الملائكة، كلما مرَّ بسماءٍ سأله ملائكتُها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ [سبأ:23]، فيقولون كلهم مثلما قال جبريل، فينتهي جبريلُ بالوحي إلى حيث أمره الله
“Apabila Allah hendak mewahyukan perintah-Nya, maka Dia firmankan wahyu tersebut. Langit-langit bergetar dengan kerasnya karena takut kepada Allah. Dan ketika para malaikat mendengar firman tersebut, mereka pingsan dan bersujud. Di antara mereka yang pertama kali bangun adalah Jibril. Maka Allah sampaikan wahyu yang Ia kehendaki kepada Jibril. Kemudian Jibril melewati para malaikat, setiap ia melewati langit, maka para penghuninya bertanya kepadanya, “Apa yang telah Allah firmankan kepadamu?” Jibril menjawab, “Dia firmankan yang benar, dan Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.” Dan seluruh malaikat yang ia lewati bertanya kepadanya seperti pertanyaan pertama. Demikianlah sehingga Jibril menyampaikan wahyu tersebut sesuai dengan yang telah diperintahkan oleh Allah kepadanya.” (Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Thabrani, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahumullah).
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah di dalam Al-Fatawaa menyebutkan,
ومذهب سلف الأمة وأئمتها وخلفها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل، وجبريل سمعه من الله عز وجل
“Mazhab para pendahulu umat ini beserta para imamnya dan orang-orang yang mengikuti mereka adalah meyakini bahwa Nabi Muhammad mendengarkan Al-Quran dari malaikat Jibril dan Jibril mendengarnya langsung dari Allah Ta’ala”.
Begitulah Al-Quran yang mulia ini Allah turunkan kepada hamba-Nya yang paling mulia, Muhammad Shalallahu ‘alaihi wasallam. Semoga kita ditulis sebagai salah satu ahlul quran, yaitu menjadi seseorang yang senantiasa membaca Al-Quran dan hidup bersamanya. Amiin Ya Rabbal Aalamiin.
***
Penulis: Muhammad Idris, Lc.
Sumber: https://muslim.or.id/74827-bagaimanakah-al-quran-turun-kepada-nabi-muhammad.html