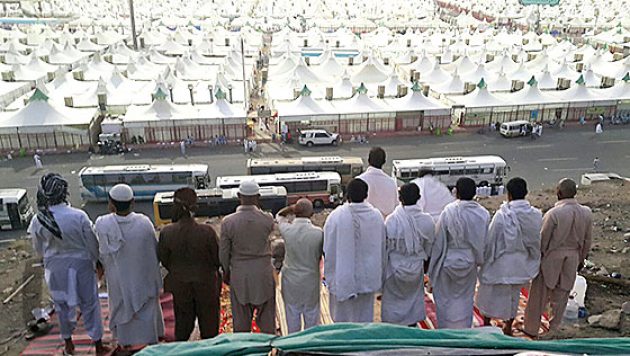SIANG itu tiba-tiba dering telepon berbunyi dari talam tasku. Oh, dari ibu. Sempat kaget mengetahuinya. Maklum, tak biasanya ibu meneleponku di saat-saat baru jam pulang sekolah. Karena ibu tahu kebiasaanku, sebelum pulang, aku biasanya shalat dulu di mushalla sekolah, kemudian istirahat sejenak.
“Assalamu’alaikum… Nak, kalau sudah selesai sekolah, langsung pulang, yah. Jangan mampir ke mana-mana!” ucap ibu dengan nada bergetar, dan langsung menutup sambungan telepon.
Terang saja, aku langsung diselimuti kekalutan. Pikiran-pikiran buruk terjadi di keluarga tiba-tiba berseliweran di benak. Ingin menelepon balik, mustahil. HP tidak ada pulsa. Akhirnya, dalam kekalutan itu, saya putuskan untuk mengerjakan shalat zuhur terlebih dahulu.
Selesai, aku langsung menuju parkiran sekolah untuk mencari tumpangan. Namun apa lacur, semua kawan sudah pada buyar. Tempat parkir sepi. Ingin naik angkutan desa, uang tak puya. Di lain sisi, suara ibu di telepon terngiang-ngiang. Semakin kalutlah pikiran.
Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya aku memutuskan pulang dengan berjalan kaki di tengah teriknya matahari. Jarak sekolah-rumahku kurang lebih 3,5 km.
Ketika langkahku telah mendekati halaman rumah, tanda-tanda firasat burukku terjadi mulai bermunculan. Nampak beberapa tetangga berjubel di rumah. Semua mata tertuju padaku. Kudapati sorot mereka penuh duka. Bekas aliran air mata masih melekat di pipi. Terutama kaum perempuan.
Ketika aku masuk ruangan utama keluarga; Innaalillah…. Sepontas terasa persendianku remuk. Jantungku seakan berhenti berdegup, ketika kusaksikan sosok di hadapanku. Ayahku yang merantau di negeri jiran, berbaring tak berdaya dengan balutan perban.
“Bapak kecelakaan kerja. Jari jemarinya terpotong, terkena mesin penggiling rumput,” ucap ibu lirih.
Duug!
Aku tersentak kaget mendengarnya. Pelopak mataku tak lagi kuasa menahan bendungan air mata. Kudekati ayah. Ia berusaha menegarkan diri dengan berupaya memberi tersenyum kepadaku. Sementara itu, air matanya pun meleleh. Kupeluk erat ayah. Suasana semakin haru. Suara tangisan membahana dari sanak keluarga.
‘Badai’ Lanjutan
Laksana kata pepatah; Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Itulah yang terjadi selanjutnya dalam keluargaku. Musibah yang menimpa bapak, justru menjadi awal retaknya keakraban hubungan keluarga.
Kakek dan nenek dari pihak ayah, tidak terima dengan kejadian menimpa ayah. Celakanya, mereka justru menyudutkan ibu sebagai biang kerok kecelakaan itu. Logika yang dipakai, musibah itu tidak akan pernah terjadi, kiranya, ayahku tidak menikah dengan ibu.
Karena pernikahan itulah, ayah harus merantau jauh ke Malaysia, demi memenuhi kehidupan keluarga, yang akhirnya menerima kenyataan, ia mengalami lumpuh permanen karena kecelakaan kerja.
Ayah sudah beberapa kali berusaha memberikan pemahaman kakek dan nenek. Namun tak jua mengerti. Mereka masih saja memusuhi ibu. Puncaknya, merasa tidak kuat terus dipojokkan, ibu menggugat cerai.
Ayah berusaha meredam keinginan ibu, tapi gagal. Beberapa alasan dikedepankan, termasuk keberlangsungan nasib kami, sebagai anaknya, bila harus bercerai, tidak mempan mendinginkan suasana.
Akhirnya, peristiwa yang paling kutakutkan itu pun terjadi. Ibu dan ayah resmi bercerai. Kejadian itu terjadi menjelang Ramadhan. Ayah menjatuhkan talak satu pada ibu. Jadilah Ramadhan tahun itu, kami lalui sekeluarga tanpa kehadiran ibu.
Saya yang masih usia remaja (lulusan SMP) semakin kalut pikiran. Semua menjadi sasaran amarahku. Tak kecuali Tuhan (Allah). Kutuntut keadilan-Nya, yang kurasakan tak menghinggapi keluargaku.
Berkah Bulan Suci
Syukur Alhamdulillah, kekeliruanku ini tak berjalan lama. Pasalnya, ustadz tempatku belajar al-Qur’an terus memberiku pencerahan. Yang paling menghentakku, ketika beliau menyitir ayat al-Qur’an yang berbunyi;
“Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya maka ia berkata. Tuhan telah menghinaku.” (QS Al-Fajr : 16)
Aku benar-benar terasa tersindir dengan ayat ini. bergegas kuberistighfar, mengakui kesalahan. Aku pun mulai menata hati untuk ridha atas apa yang Allah tetapkan untuk kami sekeluarga.
Di lain pihak, ayah sendiri menuntun kami sekeluarga, untuk mengoptimalkan keberkahan bulan suci Ramadhan, guna bermunajat kepada-Nya, memohon, agar keberkahan senantiasa menaungi keluarga kami.
Kami pun mengamini ayah. Terlihat ayah sangat tekun beribadah. Begitupun dengan diriku. Setiap kali selesai melakukan ibadah, khususnya shalat, selalu kuselipkan doa untuk keutuhan rumah tangga kami.
“Ya Allah, persatukanlah kembali ibu dan ayah kami, dan berkahilah keluarga kami,” demikianlah di antara untaian doa yang kupanjatkan kepada-Nya.
Laa haulaa wa laa quwwata illa billahil azhim. Allah ternyata mendengarkan rintihan kami sekeluarga. Di penghujung Ramadhan, ibu bertandang ke rumah, dan menyatakan permintaan maaf kepada ayah, dan meminta untuk rujuk kembali.
Ayah pun dengan lapang dada memaafkan ibu. Idul Fitri itu pun akhirnya kami lalui dengan hati nan riang gembira. Tak sampai di situ kebahagiaan kami. Tak lama berselang, bapak mendapat panggilan dari tempat kerjanya semula, dari Malaysia.
Dijanjikan ia akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisinya, sekaligus mendapat gaji yang berlipat. Berangkatlah ayah. Dari hasil keringat ayah itu pulalah, akhirnya, keluarga kami bisa menyambung hidup. Termasuk aku, bisa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
Terimakasih, ya Allah, atas karunia yang kau limpahkan atas keluarga kami.*
Dikisahkan oleh Hasbi kepada Muhammad Syahroni (Anggota komunitas menulis PENA Gresik)
HIDAYATULLAH